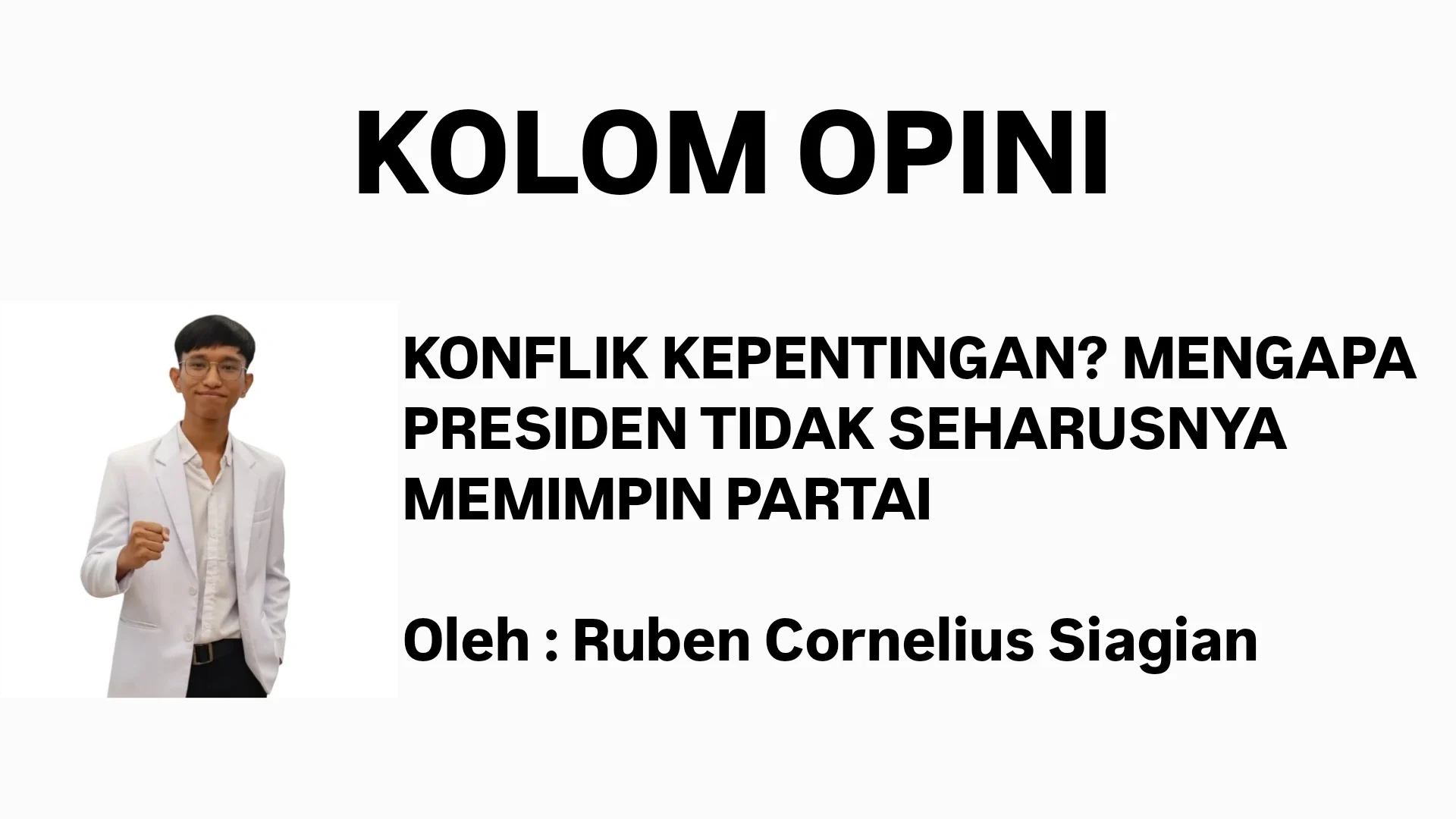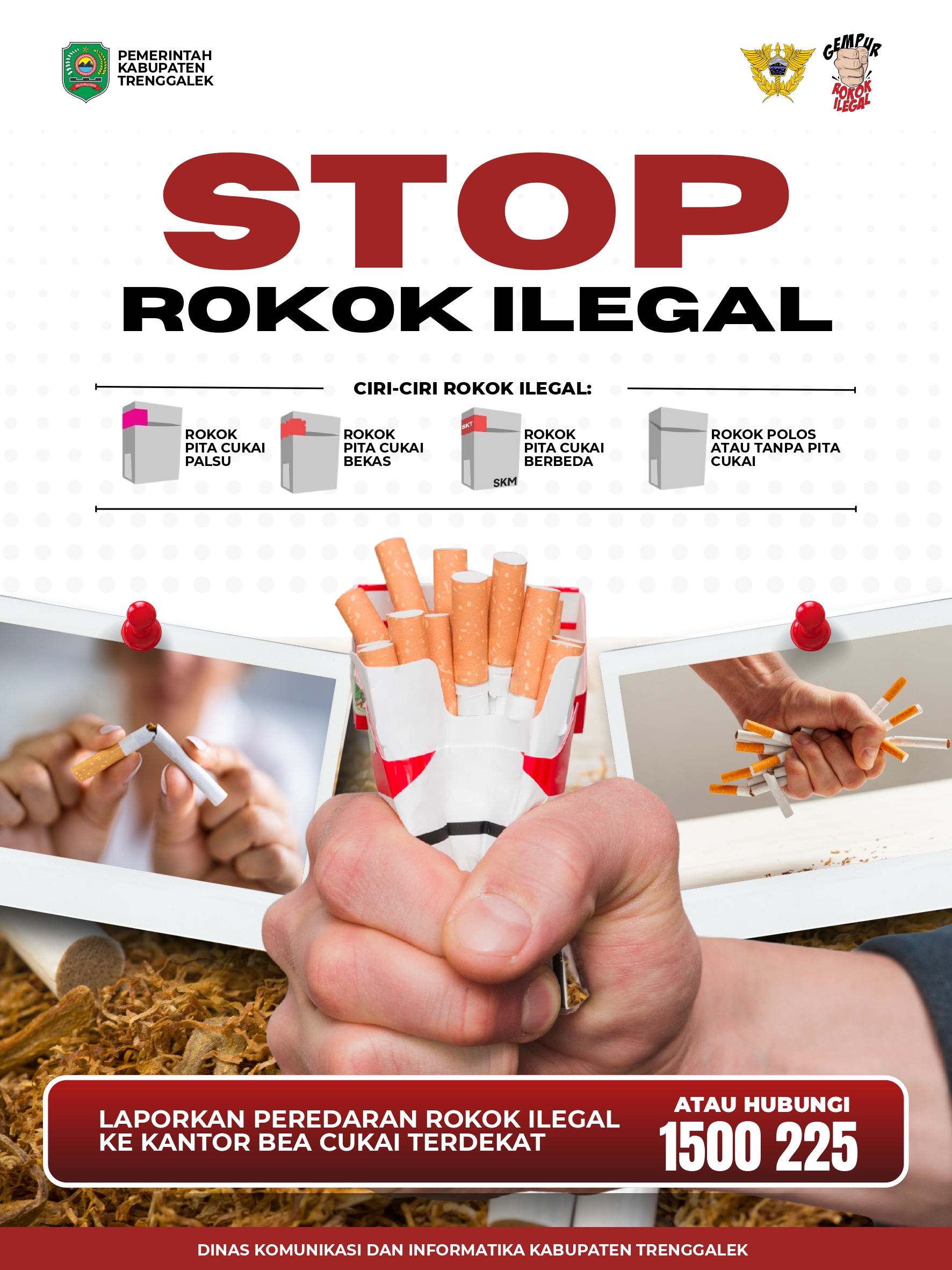Pengantar
Demokrasi modern menempatkan presiden bukan hanya sebagai kepala pemerintahan, tetapi juga sebagai simbol pemersatu bangsa. Di dalam sistem presidensial seperti Indonesia, presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga legitimasi politiknya berasal dari kedaulatan rakyat, bukan dari mandat partai politik semata. Namun, dalam praktik politik, sering muncul persoalan ketika presiden merangkap sebagai ketua partai politik.
Namun kita perlu bertanya, apakah seorang presiden masih dapat menjaga netralitasnya jika ia juga memimpin partai yang jelas memiliki kepentingan elektoral? Apakah keputusan-keputusan yang dibuatnya sungguh didasarkan pada kepentingan bangsa, atau justru diarahkan untuk memperkuat hegemoninya melalui kendaraan partai?
Persoalan ini bukan sekadar teknis, melainkan menyentuh aspek fundamental dari demokrasi konstitusional, yaitu pembagian kekuasaan, netralitas lembaga negara, dan keadilan politik. Montesquieu, dengan teorinya tentang trias politica, telah mengingatkan sejak abad ke-18 bahwa kekuasaan yang terkonsentrasi pada satu tangan akan melahirkan tirani. Dalam konteks Indonesia, potensi konsentrasi kekuasaan itu semakin nyata ketika presiden juga menjadi pemimpin partai besar.
UUD 1945 memberikan mandat besar kepada presiden. Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (Pasal 4), presiden memegang kekuasaan eksekutif, memimpin kabinet, dan berperan dalam perumusan kebijakan nasional. Yang menarik, mandat tersebut diberikan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A), bukan oleh partai politik. Artinya, secara filosofis, presiden bertanggung jawab kepada seluruh warga negara, bukan hanya kepada konstituen partainya.
Namun, jika presiden juga menjabat sebagai ketua partai, maka garis demarkasi antara “kepentingan negara” dan “kepentingan partai” menjadi kabur. Konflik kepentingan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, yaitu dalam pengambilan keputusan anggaran, penunjukan pejabat publik, hingga distribusi proyek pembangunan.
Penelitian yang dilakukan oleh Mietzner, M. (2023) dan Nazaruddin, M., Kamil, A. I., & Aulia, F. (2023) menegaskan bahwa presiden Indonesia sejatinya diharapkan menjadi simbol persatuan, bukan simbol kepentingan partisan. Sementara Keller, J. W., & Foster, D. M. (2012) mengingatkan bahwa gaya kepemimpinan presiden yang terikat pada afiliasi politik sering kali mengurangi kapasitasnya sebagai pemimpin yang netral. Dengan kata lain, netralitas konstitusional presiden rawan tereduksi jika ia juga memimpin partai.
Demokrasi atau Dominasi Kekuasaan?
Salah satu pilar fundamental dalam demokrasi adalah mekanisme checks and balances, di mana kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus saling mengawasi dan mengimbangi agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Prinsip ini menjadi kunci agar kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu aktor politik. Namun, keseimbangan tersebut akan mudah terganggu ketika seorang presiden tidak hanya memegang kekuasaan eksekutif, tetapi juga menguasai partai yang dominan di parlemen. Dalam kondisi seperti itu, DPR cenderung kehilangan independensinya karena legislator lebih loyal kepada presiden selaku ketua partai dibandingkan kepada rakyat yang mereka wakili. Akibatnya, fungsi pengawasan yang seharusnya dijalankan oleh parlemen menjadi melemah.
Dominasi partai presiden di legislatif juga menekan keberadaan oposisi. Oposisi yang seharusnya berperan sebagai pengkritik dan pengimbang kekuasaan kehilangan ruang untuk menyuarakan alternatif kebijakan. Ketika suara kritis semakin dipersempit, kualitas demokrasi menurun karena perdebatan politik hanya berjalan di ruang yang dikendalikan oleh partai penguasa. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya potensi ketimpangan dalam arena elektoral. Presiden yang sekaligus memimpin partai memiliki akses penuh terhadap sumber daya negara, baik berupa birokrasi maupun anggaran, yang dapat dimobilisasi untuk memperkuat posisi partainya menjelang pemilu.
Penelitian yang dilakukan oleh Nur, F. A., & Wardani, S. B. E. (2024) mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menunjukkan bahwa birokrasi di Indonesia sering kali terpolitisasi dalam kontestasi elektoral. Jika presiden merangkap sebagai ketua partai, risiko mobilisasi birokrasi demi kepentingan partisan akan semakin tinggi. Situasi ini bukan hanya mengancam kemandirian institusi demokrasi, tetapi juga merusak keadilan politik karena menciptakan lapangan permainan yang tidak setara bagi semua peserta demokrasi. Sehingga rangkap jabatan presiden sebagai pemimpin partai tidak sekadar persoalan etika politik, melainkan ancaman serius terhadap integritas demokrasi itu sendiri.
Perbandingan Internasional
Dalam kerangka comparative constitutional law, pengalaman lintas negara menunjukkan variasi yang sangat signifikan mengenai relasi antara presiden dan partai politik. Di Amerika Serikat, meskipun presiden berasal dari partai tertentu, ia tidak pernah memegang jabatan sebagai ketua partai. Setelah terpilih, kedudukannya bertransformasi dari kandidat partisan menjadi simbol persatuan seluruh bangsa. Partai politik tetap memainkan peran, tetapi lebih sebagai mesin elektoral dan wadah kaderisasi, bukan sebagai instrumen yang mengontrol presiden dalam menjalankan pemerintahan.
Berbeda dengan itu, di Jerman, praktik politik menegaskan adanya pemisahan peran. Kanselir yang berasal dari partai politik umumnya melepaskan jabatannya sebagai ketua partai setelah terpilih. Angela Merkel, misalnya, tetap memiliki pengaruh besar di dalam partai CDU, namun secara institusional ia memisahkan kepentingan partai dari kewajibannya sebagai kepala pemerintahan. Sehingga integritas eksekutif tetap terjaga dari dominasi partisan.
Prancis mengambil langkah lebih tegas melalui sistem semi-presidensialnya. Konstitusi secara eksplisit melarang presiden merangkap jabatan di partai, sehingga setiap presiden ditempatkan dalam posisi netral demi menjaga legitimasi demokrasi. Aturan ini memastikan agar kekuasaan negara tidak diperalat untuk memperkuat basis elektoral presiden maupun partainya.
Sebaliknya, praktik di Rusia dan Turki memberikan contoh kontras tentang bahaya rangkap jabatan presiden dan ketua partai. Vladimir Putin dengan United Russia serta Recep Tayyip Erdoğan dengan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) menunjukkan bagaimana presiden yang sekaligus mengendalikan partai dapat mengonsolidasikan kekuasaan hampir tanpa batas. Konsekuensinya adalah pelemahan oposisi, terkikisnya independensi media, serta tergerusnya kemandirian lembaga yudikatif.China menghadirkan bentuk yang lebih ekstrem lagi. Dalam sistem satu partai, pemimpin negara otomatis adalah pemimpin partai, dan partai pada akhirnya identik dengan negara. Konfigurasi ini menghapuskan oposisi dan menghilangkan mekanisme pengawasan, sehingga rangkap jabatan menjadi bagian integral dari struktur otoritarianisme.Dari perbandingan lintas negara tersebut terlihat pola yang jelas. Negara-negara demokratis mapan cenderung memisahkan kepemimpinan presiden dari kepemimpinan partai, dengan tujuan menjaga netralitas dan keadilan politik. Sebaliknya, negara-negara dengan kecenderungan otoritarian justru meleburkan keduanya, menjadikan presiden sekaligus ketua partai sebagai pusat kekuasaan tanpa kontrol yang memadai. Sehingga rangkap jabatan presiden dan ketua partai lebih dekat dengan pola otoritarianisme ketimbang praktik demokrasi yang sehat.
Implikasi bagi Demokrasi Indonesia
Jika praktik presiden merangkap sebagai ketua partai politik terus dibiarkan di Indonesia, konsekuensi yang muncul bisa sangat serius bagi masa depan demokrasi. Instrumen negara yang seharusnya netral, mulai dari birokrasi, TNI-Polri, hingga BUMN, rentan dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral semata. Hal ini berpotensi melahirkan penyalahgunaan sumber daya negara demi memperkuat posisi politik partai presiden. Pada saat yang sama, supremasi hukum juga terancam mengalami degradasi. Aparat penegak hukum bisa berada di bawah tekanan politik untuk melindungi kepentingan partai penguasa, terutama dalam kasus-kasus korupsi yang melibatkan kader atau jaringan politik presiden.
Distorsi demokrasi elektoral pun menjadi dampak lain yang tidak terelakkan. Kompetisi pemilu kehilangan esensi keadilannya karena presiden memiliki keunggulan struktural yang tidak dimiliki kandidat lain, baik dalam akses ke sumber daya negara maupun dalam mobilisasi birokrasi. Kondisi semacam ini dapat menyeret Indonesia pada potensi kemunduran demokrasi. Sejarah Orde Baru menjadi refleksi, ketika Soeharto menggunakan Golkar sebagai kendaraan kekuasaan untuk memonopoli politik dan menyingkirkan oposisi.
Pelajaran berharga dari Reformasi 1998 seharusnya menjadi peringatan bahwa dominasi partai dan negara oleh presiden bukan hanya melemahkan demokrasi, tetapi juga membuka jalan bagi authoritarian relapse. Jika praktik ini tidak segera diantisipasi, Indonesia berisiko terjebak kembali pada pola kekuasaan terpusat yang meniadakan keseimbangan politik serta mengabaikan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional.
Montesquieu, Indonesia, dan Dunia
Montesquieu menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan agar tidak terkonsentrasi. Dalam kasus Indonesia, konsentrasi kekuasaan akan semakin parah jika presiden juga ketua partai karena ia mengendalikan eksekutif sekaligus mempengaruhi legislatif melalui partainya.
Jika dibandingkan dengan model negara lain, Indonesia berpotensi mengulang pola otoritarian ala Rusia, Turki, atau bahkan Orde Baru, alih-alih mencontoh praktik demokrasi mapan seperti Amerika Serikat, Jerman, atau Prancis.
Dapat dilihat secara comparative constitutional law, jelas bahwa praktik rangkap jabatan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional modern, yang menuntut presiden untuk berdiri di atas kepentingan partai demi menjaga impartiality dan legitimasi.
Solusi dan Rekomendasi
Untuk memperkuat demokrasi Indonesia dan mencegah konsentrasi kekuasaan yang berlebihan, diperlukan serangkaian langkah reformasi yang menyeluruh dan konsisten.
Pertama, perlu adanya reformasi hukum melalui amandemen UUD 1945 ataupun perubahan undang-undang kepemiluan yang secara tegas melarang presiden merangkap jabatan sebagai ketua partai politik. Aturan ini demi menjaga netralitas kepala negara dan menghindarkan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan partisan.
Yang kedua mekanisme nonaktif juga perlu diterapkan, di mana presiden yang terpilih wajib menanggalkan jabatan kepartaiannya selama masa kepresidenan berlangsung. Sehingga kebijakan publik yang diambil tidak akan bias dan tetap berpihak pada kepentingan rakyat secara keseluruhan.
Dan yang ketiga adalah memperkuat lembaga-lembaga pengawas seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ombudsman. Lembaga-lembaga ini harus diberi kewenangan yang lebih luas serta independensi yang kuat agar dapat memantau, menindak, dan mencegah potensi konflik kepentingan antara kekuasaan negara dan kepentingan partai politik.
Adapun sangat diperlukan revitalisasi peran oposisi. Oposisi harus tetap dijaga agar kuat dan dilindungi secara hukum sehingga mampu menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Dengan adanya oposisi yang sehat, ruang kritik dapat tumbuh subur dan kebijakan negara dapat dikoreksi ketika melenceng dari kepentingan rakyat. Sehingga partai politik juga dituntut untuk menegakkan etika politik dengan menanamkan norma bahwa seorang presiden bukanlah milik partai, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia.
Kesadaran etis ini menjadi pondasi penting agar demokrasi tidak sekadar dijalankan secara prosedural, tetapi juga substantif, di mana kepentingan bangsa selalu ditempatkan di atas kepentingan partisan.
Penutup
Presiden adalah simbol persatuan bangsa, bukan sekadar pemimpin partai. Rangkap jabatan presiden dan ketua partai politik menimbulkan konflik kepentingan yang serius, mengaburkan batas antara kepentingan publik dan kepentingan partisan, serta membuka peluang konsolidasi kekuasaan yang berlebihan.
Sejarah dan perbandingan internasional menunjukkan bahwa praktik ini lebih dekat dengan pola otoritarianisme ketimbang demokrasi. Karena itu, Indonesia harus berani menegaskan bahwa seorang presiden tidak boleh sekaligus menjadi ketua partai.
Dan Menjadi refleksi bagi kita semua, apakah kita ingin presiden Indonesia menjadi state leader yang melayani seluruh rakyat, atau sekadar party leader yang melanggengkan kepentingan partisan? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah demokrasi kita semakin matang, atau justru tergelincir kembali ke dalam politik kekuasaan yang sempit.
Referensi
Elgie, Robert. “The French Presidency.” Developments in French Politics 5 (2013): 19–34.
Hale, Henry E. “The Origins of United Russia and the Putin Presidency: The Role of Contingency in Party-System Development.” Demokratizatsiya 12, no. 2 (2004).
Helms, Ludger. “‘Chief Executives’ and Their Parties: The Case of Germany.” German Politics 11, no. 2 (2002): 146–64.
Keller, Jonathan W, and Dennis M Foster. “Presidential Leadership Style and the Political Use of Force.” Political Psychology 33, no. 5 (2012): 581–98.
Kelmaskosu, Krisyando, and Umbu Rauta. “Kekuasaan Presiden Dalam Pembentukan Kabinet Menurut Sistem Presidensial.” Jurnal USM Law Review 8, no. 1 (2025): 143–57.
Krause, Sharon. “The Spirit of Separate Powers in Montesquieu.” The Review of Politics 62, no. 2 (2000): 231–65.
Manicas, Peter T. “Montesquieu and the Eighteenth Century Vision of the State.” History of Political Thought 2, no. 2 (1981): 313–47.
Mietzner, Marcus. The Coalitions Presidents Make: Presidential Power and Its Limits in Democratic Indonesia. Cornell University Press, 2023.
Nazaruddin, Muhammad, Ade Ikhsan Kamil, and Faizul Aulia. “Symbols and Discursive Contestation of Presidential Election in Indonesia.” Malikussaleh Social and Political Reviews 4, no. 1 (2023): 25–32.
Nur, Fitri Abidah, and Sri Budi Eko Wardani. “NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PUSARAN POLITISASI BIROKRASI DI INDONESIA.” Journal Publicuho 7, no. 2 (2024): 833–42.
Tiefer, Charles. “The Constitutionality of Independent Officers as Checks on Abuses of Executive Power.” BUL Rev. 63 (1983): 59.
Ünan Göktan, Ayşe Deniz. “The Role of Culture in Turkish Political Discourse: President Recep Tayyip Erdoğan and the Justice and Development Party.” In When Politicians Talk: The Cultural Dynamics of Public Speaking. Springer, 2021.
Wasti, Ryan Muthiara. “Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap Produk Hukum Pada Masa Pemerintahan Soeharto Di Indonesia.” Jurnal Hukum & Pembangunan 45, no. 1 (2015): 76–105.
Profil Penulis

Ruben Cornelius Siagian adalah seorang peneliti independen sekaligus pengamat politik dan kebijakan publik yang menggabungkan ketajaman akademik dengan keberanian intelektual dalam membedah isu-isu strategis di Indonesia. Lahir dan besar di Medan, ia menjalankan pendidikan sarjananya di Universitas Negeri Medan pada Program Studi Fisika Non-Pendidikan dengan peminatan utama di bidang fisika komputasi dan teoritis. Latar belakang akademiknya di ranah sains eksakta tidak membatasi kiprahnya pada ranah politik dan sosial, justru menjadi fondasi kuat yang membentuk pola berpikir analitis, kritis, serta berbasis data dalam melihat dinamika kebijakan publik dan fenomena politik kontemporer.
Sebagai penulis opini, Ruben dikenal vokal dalam mengkritisi praktik oligarki, lemahnya representasi rakyat, serta problematika korupsi di Indonesia. Melalui tulisan-tulisannya di berbagai media nasional dan platform populer, ia menyoroti isu-isu mendasar mulai dari komitmen pemerintah dalam pemberantasan korupsi, krisis demokrasi di parlemen, hingga kebutuhan reformasi dalam tata kelola publik, termasuk di sektor energi, pendidikan, dan badan usaha milik negara. Pandangannya tajam, seringkali konfrontatif, namun senantiasa berlandaskan pada argumentasi rasional yang memadukan perspektif akademik dengan sensitivitas sosial.
Konsistensinya menulis di media seperti Tatkala, Jubi, Birokrat Menulis, Epochstream, Rentak, hingga Anotasi, menunjukkan kiprahnya bukan sekadar wacana sesaat, melainkan bagian dari komitmen intelektual yang lebih luas. Ruben menjadikan ruang publik sebagai arena dialektika untuk mengawal demokrasi, menyoroti transparansi, dan mendorong akuntabilitas negara. Pada saat yang sama, ia tetap aktif dalam riset ilmiah multidisipliner, mulai dari fisika komputasi, astronomi, nuklir, hingga analisis kebijakan berbasis data, yang karyanya terpublikasi di jurnal-jurnal nasional dan internasional.
Kiprah organisasinya pun mengintrepetasikan konsistensi kepemimpinan. Sejak masa kuliah ia aktif di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dan Senat Mahasiswa FMIPA UNIMED, hingga akhirnya dipercaya sebagai Ketua Komisariat. Perjalanan itu kemudian berlanjut ke ranah advokasi publik melalui GAMKI Sumatera Utara, serta inisiatif akademik dengan mendirikan Riset Center Cendekiawan dan Peneliti Muda Indonesia. Semua ini menunjukkan bahwa Ruben bukan hanya pengamat, melainkan juga aktor yang berkontribusi nyata dalam menggerakkan diskursus politik dan pengembangan keilmuan di tanah air.
Baik di ranah akademik maupun opini populer, Ruben Cornelius Siagian hadir sebagai figur intelektual muda yang menjembatani dunia sains dan politik, dengan satu tujuan yang jelas, yaitu mendorong reformasi struktural dan memperjuangkan kepentingan publik melalui penelitian, tulisan, dan aksi nyata.