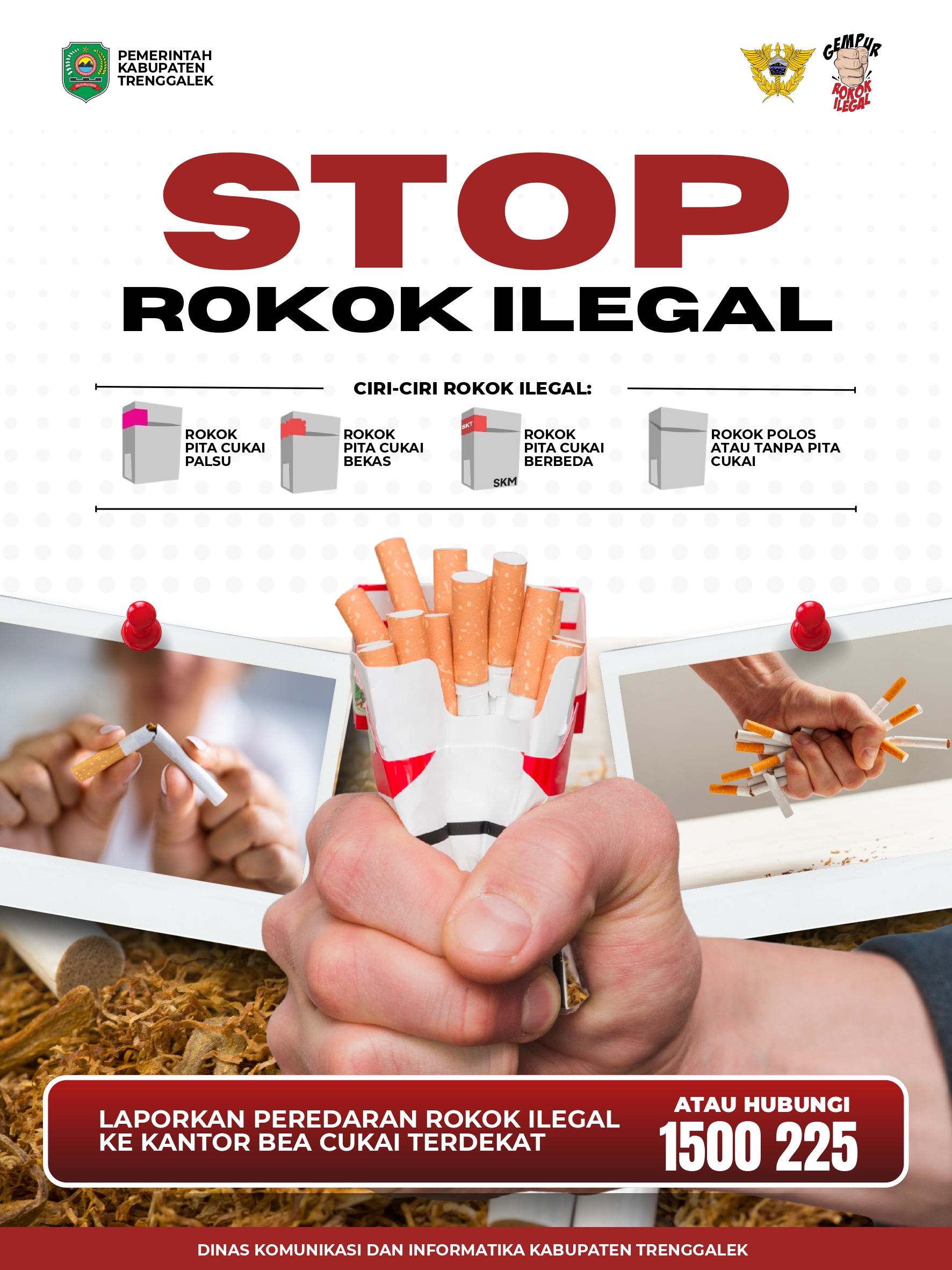Abstrak
Eksploitasi sumber daya alam di Kabupaten Trenggalek menimbulkan pertanyaan serius
mengenai keadilan distribusi manfaat dan beban ekologis. Artikel ini mengurai
ketimpangan antara potensi kekayaan tambang dan dampaknya bagi masyarakat lokal.
Dengan pendekatan analisis kebijakan dan hukum sumber daya, tulisan ini mendorong
pembaruan tata kelola Sumber Daya Alam (SDA) yang lebih adil, partisipatif, dan
berkelanjutan.
Pendahuluan
Trenggalek dikenal sebagai kabupaten dengan bentang alam indah dan potensi geologis
yang kaya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, sorotan publik lebih banyak tertuju
pada maraknya eksploitasi tambang emas dan mineral lainnya. Proyek-proyek ekstraktif
masuk melalui izin yang sebagian besar diterbitkan oleh pemerintah pusat. Di tengah janji
pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, masyarakat lokal justru kerap merasa
menjadi pihak yang dikorbankan.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan kritis:
“siapa sebenarnya yang menikmati keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam
di Trenggalek?”
Ketimpangan Manfaat dan Beban
Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) idealnya memberi manfaat ekonomi, sosial, dan
lingkungan secara seimbang. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan ketimpangan.
Izin usaha pertambangan (IUP) yang dikeluarkan sering kali minim partisipasi warga.
Bahkan, beberapa lokasi tambang menyasar kawasan lindung dan ruang hidup masyarakat
adat atau petani lokal.
Korporasi pemegang IUP mendapatkan hak untuk menambang dalam jangka panjang.
Sementara itu, masyarakat hanya menerima dampak—jalan desa rusak, polusi debu,
sumber air mengering, bahkan terjadi konflik horizontal terkait klaim lahan. Pekerjaan
yang ditawarkan pun bersifat jangka pendek dan dengan upah rendah.
Tata Kelola yang Terpusat dan Lemahnya Daerah
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba menghapus sebagian besar
kewenangan daerah dalam perizinan tambang. Hal ini membuat kabupaten seperti
Trenggalek hanya menjadi penonton dalam proses yang menentukan masa depan
ekologisnya. Fungsi pengawasan oleh pemda pun terbatas, terutama dalam konteks
kapasitas teknis dan anggaran.
Moh Husni Tahir Hamid ———– PARTAI HANURA KAB.TRENGGALEK
Lebih dari itu, kontribusi langsung dari sektor tambang ke pendapatan daerah juga sangat
minim. Skema bagi hasil atau dana kompensasi tidak sebanding dengan kerusakan
lingkungan yang muncul. Inilah bentuk paradoks kebijakan: daerah menanggung risiko,
sementara keuntungan lebih banyak dinikmati di luar daerah.
Rekomendasi: Membangun Keadilan Sumber Daya Alam (SDA)
Pemerintah daerah bersama masyarakat sipil perlu membangun narasi alternatif
pembangunan yang tidak bergantung pada ekstraksi Sumber Daya Alam (SDA). Beberapa
langkah strategis yang dapat diambil antara lain:
1. Audit dan Review Izin Tambang: Melibatkan unsur perguruan tinggi, masyarakat adat,
dan organisasi lingkungan hidup.
2. Penguatan Regulasi Perlindungan Lingkungan Daerah: Perda RTRW, Perda
Perlindungan Hutan, dan Perbup mengenai konsultasi publik perlu diperkuat
implementasinya.
3. Pengembangan Ekonomi Alternatif: Investasi pada sektor pertanian berkelanjutan,
ekowisata, dan ekonomi kreatif berbasis lokal.
4. Desentralisasi Asimetris SDA: Mendorong revisi UU Minerba agar daerah penghasil
memiliki porsi kewenangan lebih besar dalam mengatur wilayahnya.
Penutup
Kekayaan alam Trenggalek seharusnya menjadi anugerah, bukan kutukan. Ketika logika
investasi lebih mendominasi dibanding logika keberlanjutan dan keadilan sosial, maka
konflik akan terus berulang. Eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) tanpa kendali hanya
akan memperbesar jurang ketimpangan. Pertanyaannya kini bukan sekadar siapa yang
menambang, tetapi: siapa yang peduli dan siapa yang berani menghentikan ketimpangan?
Daftar Pustaka
• Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
• Wicaksono, A. (2021). SDA dan Keadilan Ekologis. Jurnal Hukum dan Lingkungan
• KPK. (2022). Kajian Tata Kelola Pertambangan di Daerah
• WALHI Jawa Timur. (2023). Laporan Advokasi Tambang Trenggalek
• BPS Trenggalek. (2024). Statistik Lingkungan Hidup dan Ekonomi Daerah
Menaksopal, 9Juli2025/13Muharram1447H