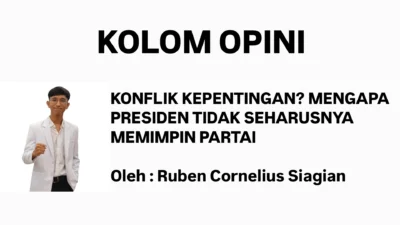Pengantar
Peringatan G30S/PKI seringkali hanya berhenti pada narasi tragedi masa lalu, digambarkan sebagai ancaman mutlak dari ideologi kiri yang harus dihapuskan. Namun, jika kita menelaah lebih dalam, sejarah seharusnya bukan sekadar alat legitimasi untuk menakut-nakuti atau membungkam pemikiran tertentu, melainkan panggilan untuk refleksi. Peristiwa itu mengingatkan kita bahwa demokrasi bukan hanya tentang ritual pemilu atau simbol-simbol kebebasan, tetapi juga tentang bagaimana suara masyarakat, terutama mereka yang lemah secara ekonomi, benar-benar dihargai dan diperhatikan. Di tengah realitas kontemporer, ketimpangan sosial dan penindasan kelas pekerja masih berlangsung, meski dalam bentuk yang lebih halus seperti penggusuran, eksploitasi buruh, dan dominasi pasar oleh segelintir elit. Mengingat hal ini, penting bagi kita untuk merenung, apakah demokrasi yang kita rayakan hari ini sungguh mampu menyeimbangkan keadilan sosial dan kebebasan ideologi, ataukah ia justru menjadi alat untuk mempertahankan status quo ekonomi dan politik yang timpang?
Kurangnya Representasi Ideologi Kiri
Dalam lanskap politik Indonesia saat ini, terlihat jelas dominasi ideologi neoliberal yang menekankan pertumbuhan ekonomi dan kepentingan pasar sebagai prioritas utama, sementara agenda keadilan sosial kerap tersingkir. Seperti dicatat oleh David Harvey dalam bukunya yang berjudul A Brief History of Neoliberalism, neoliberalisme secara sistematis menempatkan akumulasi kapital di atas kesejahteraan masyarakat, menghasilkan ketimpangan yang melebar dan meminggirkan kelompok pekerja serta rakyat miskin.[1] Di Indonesia, praktik ini terlihat dalam berbagai kebijakan ekonomi, seperti deregulasi pertambangan dan perkebunan, yang sering menguntungkan investor besar namun mengorbankan hak-hak masyarakat lokal, termasuk tanah adat dan akses terhadap sumber daya alam.
Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa tokoh-tokoh atau kelompok yang menekankan keadilan sosial atau alternatif ekonomi nonkapitalis sering dibungkam melalui stigma ideologi. Kasus seperti pelarangan partai-partai kiri pasca peristiwa G30S/PKI, serta kriminalisasi aktivis buruh dan mahasiswa yang menuntut redistribusi sumber daya, memperlihatkan bagaimana ideologi kiri distereotipkan sebagai ancaman. Antonio Gramsci, dalam teori hegemoninya, menegaskan bahwa kekuasaan tidak hanya dijalankan melalui kontrol negara, tetapi juga melalui dominasi wacana dan nilai budaya, artinya masyarakat diajarkan untuk menormalisasi sistem yang timpang dan menganggap kritik terhadap kapitalisme sebagai radikal atau berbahaya.[2]
Fenomena ini diperkuat oleh tulisan-tulisan publik seperti karya Howard Zinn dalam A People’s History of the United States, yang menekankan bagaimana narasi sejarah resmi sering mengabaikan perlawanan rakyat dan perjuangan kelas demi melanggengkan kepentingan elit.[3] Di Indonesia, efeknya tampak dalam minimnya representasi ideologi kiri dalam parlemen, media arus utama, dan kurikulum pendidikan, sehingga wacana keadilan sosial sulit menembus opini publik dan tetap berada di pinggiran diskursus politik.
Kita perlu bertanya bahwa jika demokrasi diklaim berjalan di negeri ini, mengapa ruang bagi pemikiran yang menekankan kesejahteraan kolektif dan redistribusi sumber daya tetap terbatas? Bukankah demokrasi yang sesungguhnya harus mampu menampung perbedaan ideologis dan menyeimbangkan kepentingan elit dengan kebutuhan rakyat banyak?
Demokrasi yang Tidak Sepenuhnya Inklusif
Demokrasi di Indonesia, meski berjalan melalui mekanisme formal seperti pemilu dan parlemen, sering kali hanya menjadi simbol legitimasi politik tanpa menjamin keadilan sosial yang nyata. Teori demokrasi deliberatif yang dikemukakan oleh Jürgen Habermas menekankan bahwa demokrasi sejati tidak hanya menuntut partisipasi formal, tetapi juga komunikasi yang inklusif dan deliberasi publik yang memungkinkan semua suara, terutama dari kelompok yang terpinggirkan, didengar dan dipertimbangkan.[4] Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan kontras yang tajam. Buruh di sektor industri sering mengalami upah yang stagnan sementara harga kebutuhan pokok meningkat, petani kecil kehilangan tanahnya akibat proyek pembangunan atau investasi swasta, dan komunitas miskin perkotaan menghadapi penggusuran demi kepentingan komersial. Semua itu terjadi meski secara formal mereka memiliki hak pilih dalam pemilu.
Kasus penggusuran di kampung-kampung kota besar seperti Jakarta dan Surabaya, atau konflik lahan di pedesaan seperti di Karawang dan Lampung, menunjukkan bahwa demokrasi formal tanpa perlindungan terhadap hak ekonomi dan sosial tetap tidak adil. Seperti yang ditegaskan oleh Amartya Sen dalam bukunya Development as Freedom, kebebasan politik hanya bermakna jika diiringi kebebasan ekonomi dan sosial, bahwa tanpa itu, demokrasi menjadi hampa, dan ketidaksetaraan tetap direproduksi.[5] Sehingga dari ini hak pilih semata tidak cukup, bahwa demokrasi sejati harus mampu menjamin bahwa setiap warga, terutama yang termarjinalkan, memiliki akses terhadap sumber daya, perlindungan hukum, dan kesempatan untuk hidup layak.
Fenomena ini mengajak kita merenung, bahwa apakah kita benar-benar hidup dalam demokrasi yang adil, ataukah demokrasi kita sebagian besar melayani kepentingan elit dan struktur ekonomi yang timpang? Refleksi semacam ini penting agar demokrasi tidak hanya menjadi ritual formal, tetapi juga alat untuk menegakkan keadilan sosial dan ekonomi yang substantif.
Ketimpangan dan Penindasan
Ketimpangan sosial di Indonesia hari ini sering muncul bukan sebagai konsekuensi alami, melainkan sebagai hasil dari struktur ekonomi yang secara sistematis menguntungkan segelintir elit sambil menekan mayoritas rakyat. Fenomena PHK massal di berbagai sektor industri telah menunjukkan bagaimana modal dan tenaga kerja sering berada dalam ketegangan yang timpang, hal ini memperlihatkan bahwa perusahaan berfokus pada efisiensi dan laba, sementara pekerja menjadi korban sistem yang seolah menjunjung kebebasan formal, tetapi gagal menjamin keadilan sosial. Kasus penggusuran paksa di sejumlah kota besar, seperti Jakarta dan Surabaya, menjadi bukti nyata bagaimana hak atas rumah dan ruang hidup sering dikalahkan oleh kepentingan kapitalis, meski konstitusi menjamin hak atas perlindungan dan kesejahteraan.
Dari perspektif teori Marxian, ketimpangan ini adalah refleksi dari akumulasi kapital yang menempatkan buruh pada posisi subordinat. Karl Marx dalam Das Kapital menekankan bagaimana kapitalisme cenderung menciptakan relasi eksploitasi di mana sebagian kecil pemilik modal menikmati hasil produksi, sementara mayoritas pekerja hanya memperoleh upah yang jauh dari nilai kerja mereka.[6] Hal ini sejalan dengan pengamatan Thomas Piketty dalam Capital in the Twenty-First Century, yang menunjukkan bagaimana konsentrasi kekayaan semakin membesar dan memperkuat dominasi kelompok elit, sehingga ketidaksetaraan menjadi sistemik dan sulit diatasi hanya melalui mekanisme demokrasi formal.[7]
Akses terhadap pendidikan dan layanan publik juga menjadi medan pertarungan ketimpangan. Anak-anak dari keluarga miskin seringkali menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pendidikan berkualitas, sementara anak-anak dari keluarga mampu menikmati fasilitas yang jauh lebih baik, memperkuat reproduksi kelas sosial. Ini memperlihatkan bahwa kebebasan formal hak suara, kebebasan berekspresi, atau perlindungan hukum tidak selalu selaras dengan keadilan sosial. Sejumlah peneliti, termasuk Amartya Sen dalam Development as Freedom , menekankan bahwa kebebasan sejati hanya bisa tercapai bila masyarakat memiliki akses yang setara terhadap sumber daya dasar, pendidikan, dan peluang ekonomi.[8]
Ketimpangan dan penindasan ini, jika dibiarkan, bukan hanya mengancam stabilitas sosial, tetapi juga melemahkan esensi demokrasi itu sendiri. Demokrasi yang hanya menekankan prosedur formal tanpa memperhatikan distribusi kekuasaan dan kesejahteraan nyata bagi rakyat kecil, pada akhirnya menjadi alat legitimasi bagi sistem yang timpang. Oleh karena itu, refleksi kritis terhadap struktur ekonomi dan kekuasaan adalah langkah penting untuk memastikan bahwa kebebasan tidak hanya menjadi simbol, tetapi juga nyata dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.
Refleksi
Refleksi atas peristiwa G30S/PKI seharusnya menuntun kita pada pemahaman yang lebih luas tentang demokrasi dan pluralitas ideologi, bukan sekadar sebagai justifikasi untuk menyingkirkan pemikiran kiri. Sejarah telah mengajarkan bahwa penindasan ideologis sering muncul bukan hanya karena ancaman nyata, tetapi juga karena ketakutan elit politik terhadap perubahan sosial yang menantang ketimpangan ekonomi. Menurut teori Antonio Gramsci tentang hegemoni, dominasi ideologi bukan hanya terjadi melalui kekerasan, tetapi juga melalui kontrol budaya dan wacana yang membuat masyarakat menerima status quo sebagai sesuatu yang “alami”. Dalam Indonesia, pelabelan kiri sebagai “musuh negara” pasca-1965 telah menutup ruang publik bagi kritik yang menekankan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih merata.
Demokrasi yang sehat sejatinya tidak cukup dengan formalitas institusi atau mekanisme pemilu semata, tetapi harus mampu memberi ruang bagi semua kelompok untuk mengemukakan pandangan, termasuk mereka yang menuntut reformasi struktural terhadap ketimpangan. Kasus-kasus kontemporer, seperti penggusuran warga oleh pengembang besar di Jakarta atau eksploitasi buruh migran di sektor industri, menunjukkan bahwa kebebasan formal seringkali tidak sejalan dengan keadilan sosial. Tulisan-tulisan klasik, seperti “The Road to Serfdom” karya Friedrich Hayek maupun kritik Marxian terhadap kapitalisme modern, menekankan bahwa sistem yang mengabaikan keseimbangan sosial cenderung menciptakan penindasan terselubung.
Oleh karena itu, refleksi kita terhadap G30S/PKI harus membuka kesadaran bahwa ideologi kiri sebagaimana ideologi lain yang bisa menjadi alat untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat luas, bukan ancaman mutlak bagi bangsa. Menutup ruang ideologis sama artinya dengan menutup kemungkinan demokrasi itu menegakkan keadilan secara substantif. Demokrasi yang sesungguhnya adalah demokrasi yang menampung kritik, menyeimbangkan kepentingan, dan memberi perlindungan bagi semua kelompok, termasuk mereka yang berani mempertanyakan dominasi ekonomi dan sosial. Sehingga sejarah bukan sekadar pelajaran masa lalu, melainkan lensa untuk merenungkan sejauh mana sistem kita kini mampu menyeimbangkan kebebasan politik dengan keadilan sosial.
Daftar Pustaka
Cohen, Robert, and Sonia E Murrow. Rethinking America’s Past: Howard Zinn’s A People’s History of the United States in the Classroom and Beyond. University of Georgia Press, 2021.
Fontana, Benedetto. “Hegemony and Power in Gramsci.” In Hegemony. Routledge, 2008.
Harvey, David. A Brief History of Neoliberalism. Oxford university press, 2007.
Miletzki, Janna, and Nick Broten. An Analysis of Amartya Sen’s Development as Freedom. Macat Library, 2017.
Piketty, Thomas. Capital in the Twenty-First Century. Harvard University Press, 2014.
Sen, Amartya. “Development as Freedom (1999).” The Globalization and Development Reader: Perspectives on Development and Global Change 525 (2014).
Tsoulfidis, Lefteris. “Karl Marx’s Das Kapital.” In Competing Schools of Economic Thought: Retrospect and Prospect. Springer, 2024.
Vitale, Denise. “Between Deliberative and Participatory Democracy: A Contribution on Habermas.” Philosophy & Social Criticism 32, no. 6 (2006): 739–66.
[1] Harvey, A Brief History of Neoliberalism.
[2] Fontana, “Hegemony and Power in Gramsci.”
[3] Cohen and Murrow, Rethinking America’s Past: Howard Zinn’s A People’s History of the United States in the Classroom and Beyond.
[4] Vitale, “Between Deliberative and Participatory Democracy: A Contribution on Habermas.”
[5] Sen, “Development as Freedom (1999).”
[6] Tsoulfidis, “Karl Marx’s Das Kapital.”
[7] Piketty, Capital in the Twenty-First Century.
[8] Miletzki and Broten, An Analysis of Amartya Sen’s Development as Freedom.
Profil Penulis

Dalam ranah penelitian, Ruben memiliki publikasi luas di bidang fisika komputasi, astronomi, nuklir, geologi, matematika, dan analisis sosial serta kebijakan internasional, termasuk kajian radiasi, energi nuklir, dan dinamika politik global. Selain itu, ia aktif dalam organisasi mahasiswa dan advokasi, menjabat berbagai posisi kepemimpinan di GMKI, Senat Mahasiswa FMIPA UNIMED, dan Lembaga Advokasi Pemilu GAMKI Sumatera Utara, menggabungkan kepemimpinan, riset, dan analisis kritis sebagai bagian dari kiprahnya yang multidisiplin